Senin, 25 Oktober 2010
They’re Mindboggling, They’re Absurd, and…They’re Asians !
20th Century Boys (2008)
Sabtu, 23 Oktober 2010
Eat Pray Love (2010)
Sabtu, 16 Oktober 2010
Dancer in the Dark (2000)
Kamis, 14 Oktober 2010
Stranger Than FIction (2006)
Selasa, 12 Oktober 2010
Little Miss Sunshine (2006)
Minggu, 10 Oktober 2010
Oldboy (2003)
Sabtu, 09 Oktober 2010
High School Musical 2
Disney memang sudah terkenal akan film-film remajanya, baik dengan label “Disney Channel Original Movie” atau melalui “Walt Disney Pictures”. Produktivitas mereka membuat film tidak perlu ditanya lagi, sebagai contoh sebut saja “Hannah Montana : The Movie”, “Jonas Brothers : The 3D Concert Experience”, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling banyak diingat penonton, khususnya di Indonesia, adalah film arahan Kenny Ortega, “High School Musical” (2006), yang mampu menarik sekitar 225 juta penonton di seluruh dunia. Hanya berselang 1 tahun dari filmnya yang pertama, sekuelnya yang diberi nama “High School Musical 2” diluncurkan ke publik, dan disini saya hanya akan mereview sekuelnya saja (jangan biarkan saya tersiksa untuk yang kedua kalinya dengan mereview film pertamanya).
Sekuelnya ini berkisar pada kegiatan para Wildcats dalam mengisi liburan musim panas mereka dengan bekerja sambilan di sebuah klub bernama Lava Springs. Bermacam-macam alasan yang mendorong mereka mencoba bekerja, seperti ingin menabung untuk membeli sebuah mobil, berbelanja di mall, dan meringankan beban biaya masuk universitas. Sayangnya, kecemburuan Sharpay (Ashley Tisdale) akan kedekatan Troy (Zac Efron) dan Gabriella (Vanessa Hudgens) membuat seluruh suasana di Lava Springs menjadi kacau balau, dan para Wildcats harus berusaha tetap solid, walaupun saat Troy terlihat menjauh dari mereka.
Jujur saja, ekspektasi saya cukup rendah terhadap film ini. Saya tidak terlalu mengharapkan cerita yang menarik, emosi yang mendalam, ataupun tampilan visual yang memukau. Entah kenapa genre film remaja selalu dipenuhi dengan hal-hal yang klise : si tampan pemain basket andalan bertemu si cantik, saling jatuh cinta, si cantik lainnya akan berusaha menyabotase jalinan cinta mereka, yang sudah bisa kita tebak pasti akan gagal dan berakhir happy ending. Aah…coba hidup kita sesimpel itu.
Anyway, film ini tidak memiliki kekuatan dari segi cerita. Kalau saya boleh memberi istilah, film ini super-duper-klise. Tidak ada hal special yang terjadi selama cerita selain penantian selama 135 menit untuk menonton kapankah Zac Efron dan Vanessa Hudgens akan saling berciuman di akhir cerita (ups…spoiler). Konflik yang terjadi sangat biasa dan antikonfliknya sangat mudah ditebak. Humor-humor yang ditawarkan dalam film ini pun tidak mampu memancing tawa, tapi malah cenderung menyebalkan dan norak. Secara keseluruhan, cerita yang ditawarkan film ini sangatlah hambar.
Akting yang dilakukan oleh para pemain disini terkesan sangat dipaksakan dan kaku. Saya juga tidak tahu, mungkin memang seperti itulah gaya humor Amerika, menggerakkan anggota tubuh saat berakting dengan berlebihan, hanya saja itu membuat mata saya menjadi “iritasi”. Pada momen yang seharusnya bisa dipoles menjadi lebih dramatis pun, malah mengalir dengan mengambang dan emosi yang dipancarkan kurang kuat.
Tapi harus saya akui, salah satu kelebihan film ini adalah koreografinya yang apik dan lagunya yang catchy. Rangkaian gerakan tarian di film ini dibawakan dengan energik dan mengalir dengan mulus. Dan memang sudah seharusnya seluruh kru berterima kasih pada tim musik film ini, karena atas jasa merekalah, film ini masih memiliki kemenarikannya tersendiri. Kombinasi antara tarian dan lagu di film ini berhasil mengangkat suasana ceria khas remaja yang meluap-luap.
Setelah 135 menit yang (terasa) panjang,beruntunglah saya tidak terlalu berharap banyak, sehingga tidak merasa dikecewakan. Yang menjadi perbedaan mencolok antara film ini dengan film-film remaja lainnya hanyalah nyanyian dan tarian energik yang muncul setiap 20 menit, dimanapun mereka berada. Film ini sebenarnya tidak terlalu buruk, jika kamu adalah tipe orang yang suka dengan film ringan dan sangat menyukai gaya tarian dan lagu mereka di High School Musical yang pertama. Tapi untuk kalian yang beranggapan bahwa film ini sangat dangkal, jangan cemas, saya ada di pihak kalian.
Dimas Dwi Adiguna
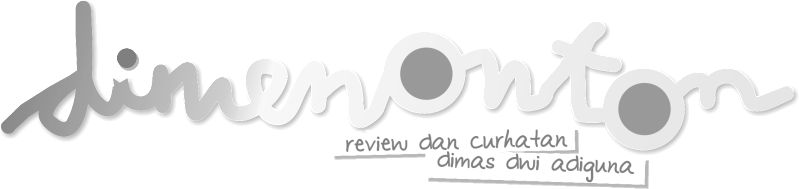

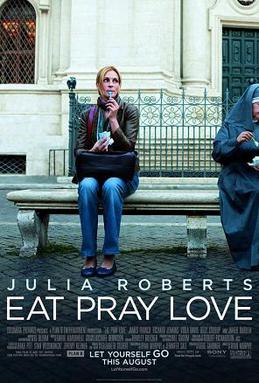



.jpg)